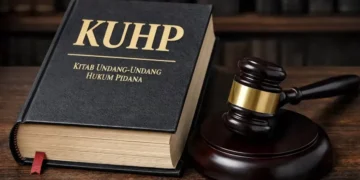Daily News | Jakarta – Sejak reformasi 1998, money politics dan kekuasaan uang di Indonesia semakin merajalela. Di era kepemimpinan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), praktik ini memang ada, tetapi tidak sebrutal sekarang.
Guru Besar UGM Yogyakarta Prof. Dr. Indra Bastian Ph. D. menjelaskan, money politics dan kekuasaan uang yang semakin mendominasi dalam perpolitikan nasional merpakan hal yang terasa antagonis. Alasannya karena pajak dari rakyat adalah sumber dari 90 persen APBN.
“Dalam teori demokrasi, ketika pajak dari masyarakat mencapai lebih dari 35-40 persen, pemerintah sudah bergantung pada rakyat,” katanya saat dihubungi KBA News, Kamis, 17 Oktober 2024.
Lulusan S2 dan S3 University of Kentucky, Amerika Serikat ini, menilai ada pemahaman yang salah ketika masyarakat dipungut pajak tinggi, membayar PBB, retribusi, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan. Padahal, sebenarnya merekalah yang membiayai pemerintah. “Namun, yang mengejutkan, justru masyarakat yang merasa bergantung kepada pemerintah. Ini yang menjadi masalah,” ungkapnya.
Dari sini, perlu mempertanyakan, ada apa dengan negara. Sebanyak 72 persen masyarakat kita hanya berpendidikan SD. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memahami bahwa mereka adalah sumber kekuatan yang membiayai pemerintah.
Sepertinya, kata dia, pemerintah sengaja mempertahankan kondisi ini. Artinya pasca reformasi hingga saat ini, kondisi tidak berbeda jauh antara tahun 2004 dan 2024. Pada 2004, ketika SBY terpilih dalam pemilu pertama pasca-reformasi, situasi yang sama sudah terjadi. “Tidak memperioritaskan peningkatan kualitas SDM rakyatnya,” tegasnya.
Seharusnya, tugas utama pemerintah adalah masalah pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lebih dari 72 persen masyarakat memiliki pendidikan di atas SMA.
“Jadi, ketika money politics marak, bukan hanya karena pragmatisme, tetapi juga karena ketidaktahuan. Masyarakat tidak paham bahwa merekalah yang membiayai pemerintah, bukan sebaliknya,” jelasnya.
Menurut dia, karena ketidaktahuan itu, masyarakat merasa ketika diberi bantuan Rp300 ribu seolah-olah dibantu oleh pemerintah. Padahal, setiap kali warga membeli barang di toko itu sudah membayar pajak 10 persen untuk negara. Setiap transaksi jual beli dipotong pajak 10 persen.
Masyarakat tidak sadar bahwa mereka sudah menyumbang jutaan rupiah kepada negara, namun hanya mendapatkan bantuan Rp300-600 ribu, dan merasa senang. Padahal, mereka juga membayar listrik yang dikenai pajak, membeli pertalite yang juga terkena pajak. “Artinya, mereka bisa menyumbang Rp12 juta tetapi hanya diberi bantuan Rp300-600 ribu, dan menganggap pemerintah baik. Ini sungguh ironis,” ungkapnya.
Prof Indra mengungkapkan, salah satu solusi menghilangkan money politics adalah rakyat harus berpendidikan, sehingga otomatis menjadi melek politik. Pendidikan atau peningkatan kualitas SDM ini merupakan tugas pemerintah.
“Pemerintah harus memahami tugasnya, yaitu melindungi tumpah darah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perbaikan kualitas SDM sesuai dengan undang-undang adalah tanggung jawab pemerintah. Ini yang seharusnya menjadi program utama,” jelasnya.
Artinya, peran pemerintah pasca reformasi hingga saat ini dalam mencerdaskan kehidupan bangsa belum berhasil alias terus gagal. Jika berhasil, pada 2030 seharusnya pendidikan warga negara minimal sudah setingkat SMA. Pada 2045, pendidikan warga seharusnya sudah mencapai level S1 atau diploma,” jelasnya. (EJP)