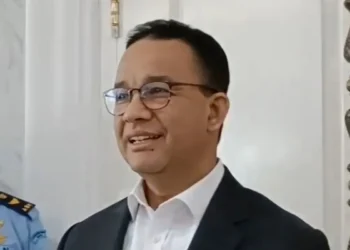Daily News | Jakarta – Pemilihan langsung yang merupakan buah dari Reformasi, ternyata tidak mampu menghadirkan substansi demokrasi. Semakin ke sini, politik uang kian merajalela. Bahkan, pemilu terakhir dianggap paling brutal dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
Dari proses pemilihan calon legislatif (caleg), calon kepala daerah (cakada), hingga calon pemimpin negara, semua seolah tidak dapat lepas dari cengkeraman politik uang, intimidasi, serta praktik pembelian suara.
Pengamat politik Assoc. Prof. Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si., pun merasakan hal itu. “Dalam kondisi yang seperti ini, Indonesia membutuhkan fatsun politik atau politik yang bermoral,” katanya saat dihubungi KBA News, Jumat, 11 Oktober 2024.
Dia menegaskan fatsun politik menjadi harapan besar bangsa ini, sebuah nilai yang dulu sudah dicontohkan oleh para pendiri republik. “Sayangnya, reformasi yang diharapkan mampu mengembalikan semangat proklamasi dalam pengelolaan negara justru bergerak ke arah yang berlawanan,” ujarnya.
Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini mengungkapkan, di sisi lain, gaya hidup hedonis di kalangan masyarakat telah mengubah kontestasi politik, seperti pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, hingga kepala daerah.
Dia mengibaratkan proses politik atau pemilihan, baik ekseskutif maupun legislatif, sudah menjadi ajang pamer kekuasaan dan politik uang. “Jelas ini sangat mencederai demokrasi di Indonesia. Maka, tugas kita semua adalah mengembalikan roda politik nasional ke jalur yang benar,” tegasnya.
Menurut dia, sebenarnya kondisi tersebut sudah dibaca oleh banyak pengamat. Tak heran muncul wacana agar pemilihan eksekutif dikembalikan pada konstitusi asli, yakni dengan menerapkan sila keempat Pancasila. Dalam sila keempat pada prinsipnya pemilihan dilakukan dengan perwakilan dan musyawarah mufakat.
Namun, ia juga menyadari bahwa sekadar kembali pada demokrasi perwakilan tidak serta-merta menjamin kondisi akan lebih baik. “Ada persyaratan tertentu yang harus diciptakan, seperti keterwakilan yang benar-benar mewakili rakyat,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti bagaimana kebijakan besar, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN), sering kali dibingkai sebagai aspirasi rakyat, meskipun dukungan yang diklaim bisa menyesatkan.
“Misalya, Presiden Jokowi, mengatakan bahwa 93% rakyat mendukung IKN karena disetujui oleh DPR,” katanya.
Khamim mengatakan, pada proses pemilihan ini, hal yang penting adalah pilar demokrasi harus ditata ulang agar tidak saling mengintervensi dan masing-masing memiliki kekuatan yang seimbang. Relasi antara negara, masyarakat, dan pemilik modal perlu diatur ulang agar tidak merugikan kepentingan bangsa Indonesia.
“Dengan demikian, demokrasi yang sejati, bukan sekadar ilusi yang digerakkan oleh kekuatan uang, dapat kembali hidup di negeri ini,” tegasnya.
Kian parah
Sementara itu, Muhammad Adi Alim, seorang aktivis demokrasi, menyatakan bahwa meskipun politik uang sudah ada sejak zaman Megawati dan SBY, saat itu belum sebar-bar seperti sekarang. “Dulu, masyarakat mungkin belum terlalu peduli dengan pesta demokrasi. Tapi sekarang, politik uang sudah merajalela di mana-mana,” ujarnya saat dihubungi KBA News, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Mantan Caleg Partai Demokrat Dapil Kulon Progo ini mengungkapkan, sebelum menyalahkan kondisi brutal yang ada saat ini, hal yang paling mendesak adalah memperbaiki mindset dan mental masyarakat. Koruptor sebenarnya sudah tercipta sebelum pemilu berlangsung, karena masyarakat sering kali meminta sesuatu terlebih dahulu kepada para kandidat.
“Jadi, kalau ada kandidat yang datang berkunjung, mereka bertanya, ‘Kamu mau kasih apa di sini? Nanti kami pilih’, itu sering terjadi,” ungkap TikToker Politik ini.
Pria yang akrab disapa Adi Marz ini mengungkapkan, Pemilu 2024 pun tidak terlepas dari fenomena ini. Bahkan lebih kejam lagi. “Masyarakat menerima semua amplop dari berbagai kandidat. Tapi soal memilih, itu urusan hati masing-masing,” jelasnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun uang diterima, suara tetap menjadi misteri. Kondisi ini bagi pelaku politik uang sebenarnya adalah bentuk perjudian yang sangat berisiko. “Sebenarnya, politik uang bagi pelakunya adalah gambling dan konyol, karena tidak ada jaminan bahwa memberi uang berarti menang,” tegasnya.
Namun, brutalitas politik uang bukan hanya soal kandidat yang memberi. Masyarakat pun perlu diubah pendekatannya. Menurut Adi, masyarakat perlu disentuh dengan berbagi pendekatan yang lebih positif. “Bisa melalui pendekatan religi, program-program nyata, atau yang lain. Di situlah seharusnya kandidat diuji, atas apa yang akan mereka tawarkan jika terpilih.”
Sayangnya, para kandidat yang rela menggelontorkan uang dalam jumlah besar menunjukkan tanda-tanda kekurangan kapasitas intelektual atau integritas. Mereka lebih mengandalkan kekuatan finansial daripada visi atau kompetensi. Hal ini disambut baik oleh “makelar suara”, sekelompok orang yang menjual suara rakyat kepada kandidat yang membayar paling tinggi. “Ini bisa dilihat dari data bahwa 60 persen anggota DPR saat ini adalah pengusaha,” lanjut Adi.
Fakta ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kualitas undang-undang yang akan dibuat oleh DPR ke depan. “Saya tidak yakin mereka bisa membuat undang-undang yang baik. Banyak dari mereka menjadi pengusaha bukan karena kemampuan intelektual, tetapi karena kekayaan yang diwarisi.”
Pertanyaan besar yang tersisa adalah: bagaimana nasib demokrasi di Indonesia ketika suara rakyat terus diperjualbelikan? Di tengah brutalitas politik uang, apakah masih ada harapan bagi perubahan nyata di negara ini? “Saya khawatir, Indonesia akan terus terperosok dalam lingkaran setan kekuasaan uang yang menggerus fondasi demokrasi,” tutur alumni UNY ini. (EJP)